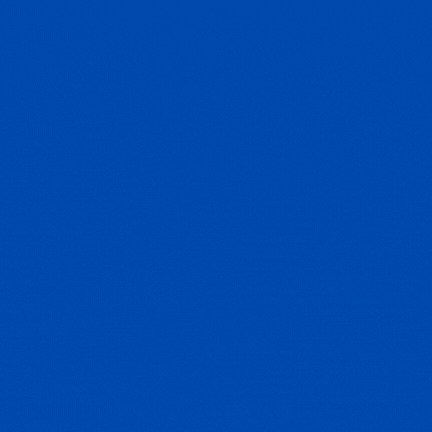Kiai Sahal adalah santri kelana yang menimba ilmu dari pesantren ke pesantren. Dari Kajen, Pati, Jawa Tengah, ia melanjutkan ngaji kepada Kiai Muhajir di Bendo, Kediri. Setelah dari Bendo, ia nyantri kepada Kiai Zubair di Sarang, Rembang serta berguru melalui korespondensi kepada Syekh Yasin al Fadani di Makkah al Mukarromah. Kiai Sahal, ulama asal Kajen, Pati, Jawa Tengah ini wafat pada Januari 2014 M/ Rabi’ul Awwal 1435 H.
Ia memiliki dua versi tahun kelahiran. Versi pertama sebagaimana tertera dalam berbagai dokumen resmi, Kiai Sahal tercatat lahir pada tahun 1937. Namun, dalam sebuah buku kecil milik ayahandanya, ditemukan catatan bahwa tahun kelahiran yang sebenarnya adalah tahun 1933. Versi kedua ini dikemudian hari terbukti lebih cocok apabila disandingkan dengan temuan-temuan lainnya. Misalnya terkait dengan usia saat Kiai Sahal ditinggal wafat oleh ayahandanya atau pada usia berapa Kiai Sahal awal mula menulis kitab, hingga pada usia berapa ia menikah.
Meski perjalanan pendidikannya dihabiskan dari pesantren ke pesantren, tidak menjadikan Kiai Sahal hadir sebagai sosok yang emoh terhadap dunia pendidikan non-pesantren. Pemikiran-pemikirannya yang terdepan dalam menyerap pemikiran kekinian di satu sisi, berjalan beriringan dengan pondasi keilmuan keislaman ala pesantren, pada sisi yang lain. Yang menarik, keterbukaan cara pandang Kiai Sahal ini, tidak hanya ditampakkannya dalam ruang diskusi atau forum-forum ilmiah. Kiai Sahal juga menunjukkan kemajuan pola pikirnya, saat berada di ruang domestik. Termasuk dalam memandang pentingnya kiprah dan pendidikan tinggi bagi perempuan (baca: istri).
Ada banyak pengetahuan berharga yang dapat diserap dari melihat kehidupan Kiai Sahal dari dekat. Bersyukur bahwa saya memiliki waktu sekitar sepuluh tahun untuk ngangsu kaweruh kepada beliau. Baik melalui kesaksian terhadap kesehariannya, maupun dari jawaban beliau mengenai persoalan-persoalan yang saya tanyakan.
Dari sepuluh tahun tersebut, terbilang empat tahun pertama, adalah waktu yang paling intens bagi saya dalam mengikuti keseharian beliau. Hal ini karena pada empat tahun pertama ini, saya masih tinggal serumah dengan beliau, dan di saat bersamaan, istri beliau, yakni Nyai Nafisah sedang dalam puncak kesibukannya. Baik sebagai anggota DewanPD RI, aktivis organisasi sosial kemasyarakatan, maupun sebagai guru sekaligus pengasuh pesantren.
Sebagai anggota DPD RI, praktis Nyai Nafisah harus membagi waktunya empat hari di Jakarta, dan tiga hari dengan berbagai kesibukan lainnya di wilayah Pati dan sekitarnya. Sedangkan Kiai Sahal, sebagai Rois ‘Am PBNU dan Ketua Umum MUI, hanya memiliki agenda sebulan sekali ke Jakarta. Selebihnya, pengurus pusatlah yang akan bertandang ke Kajen, apabila ada persolan mendesak yang harus segera diputuskan oleh Kiai Sahal.
Ada banyak hal istimewa yang saya temui dalam relasi Kiai Sahal dan Nyai Nafisah sebagai sepasang suami-istri. Meski Kiai Sahal adalah pucuk pimpinan di dua organisasi besar di Indonesia (NU dan MUI), namun beliau tidak serta merta menjadikan alasan kesibukannya untuk membuat sang istri hanya sibuk di wilayah domestik. Upaya untuk saling mendukung dan saling menguatkan tampak terlihat dari bagaimana dukungan dan kesempatan yang diberikan Kiai Sahal kepada Nyai Nafisah.
Bahkan, di tengah berbagai kesibukan keduanya, Kiai Sahal selalu menyempatkan diri untuk menunjukkan perhatiannya kepada sang istri dengan cara (yang menurut saya) cukup romantis. Hampir setiap Kamis siang, pada saat tiba jadwal Nyai Nafisah pulang dari Jakarta seusai empat hari beraktivitas di Jakarta, Kiai Sahal tampak menunggu sang istri di ruang tamu depan. Dengan wajah sumringah, sesuai waktu yang telah dijadwalkan, Kiai Sahal akan duduk di kursi di ruang tamu dengan menghadap ke halaman, menunggu sang istri datang. Sering pula, saya bersama anak sulung saya, menemani beliau sambil berbincang sekadarnya.
Menyaksikan momen-momen tersebut, adakalanya membuat saya merasa terbawa suasana. Karenanya, pernah suatu kali saya beranikan diri untuk bertanya:
“Pripun bah.. rasane ditinggal ibuk teng jakarta setiap minggu ngeten niki?” (bagaimana rasanya, ditinggal istri ke Jakarta setiap minggu begini?)
“Yo ora kepenak (Rasanya tidak enak)”, jawab Kiai Sahal lugas.
Kemudian beliau menambahkan, “Ndek biyen ibumu yo.. sering tak tinggali sibuk. Ibumu yo.. sabar (Dahulu, ibumu juga lebih sering saya tinggal sibuk bepergian, dan ibumu juga selalu bersabar). Dan jawaban beliau waktu itu, terdengar sebagai jawaban yang luar biasa bagi saya. Bahkan hingga saat ini.
Jawaban ini, menunjukkan bagaimana Kiai Sahal memiliki visi kesetaraan dalam melihat perempuan/laki-laki atau suami/istri sebagai sesama manusia yang memiliki kewajiban yang sama dalam melaksanakan fungsi domestik dan fungsi publiknya. Pada saat Kiai Sahal dalam kesibukannya, maka Nyai Nafisah memberikan dukungan sepenuh jiwa. Demikian pula saat Nyai Nafisah melaksanakan fungsinya di ranah domestik atapun publik, maka Kiai Sahal adalah orang pertama yang memberikan dukungannya.
Pada akhirnya, meski Kiai Sahal tidak tercatat sebagai aktivis perempuan, namun visi terdepan beliau dalam persoalan perempuan dapat jelas terbaca dari laku keseharian beliau. Baik terkait keputusan-keputusan besar dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam sikap keseharian dalam memberikan dukungan terhadap kiprah sang belahan jiwa, baik di bidang pendidikan, sosial, maupun politik.
Dukungan Kiai Sahal untuk Pendidikan Perempuan
Pengalaman berharga ini, saya dapatkan di tahun-tahun awal berumahtangga. Saat itu, saya adalah ibu dua anak yang masih berusia dini (2 tahun dan 5,5 tahun). Ketika anak kedua saya hampir berusia dua tahun, Kiai Sahal bertanya mengenai rencana saya melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Terus terang saya terkejut mendengar pertanyaan beliau saat itu. Bukannya saya tak ingin melanjutkan pendidikan, karena suami pun sudah lama mendorong untuk itu. Namun, terus terang, ada rasa gamang dalam hati saya, terutama terkait persoalan-persoalan domestik.”
Namun sungguh takjub hati saya, saat Kiai Sahal dawuh, “Rozin tambah-tambah pengalamane, ilmune. Mosok awakmu ora tambah-tambah. Awakmu kudu sekolah maneh ben iso ngimbangi.” Saat itu tentu saya tidak menyangka beliau memiliki cara berfikir sedemikian rupa. Betapa saat itu saya menyadari keluasan cara pandang Kiai Sahal. Beliau memaknai relasi suami-istri bukan semata mengenai bagaimana mendidik anak dan masak-memasak. Namun juga bagaimana seharusnya ada usaha untuk bisa saling memahami dunia satu sama lain.
Baca juga: Cak Nur dan Konsep Sakral-Profan Emile Durkheim
Sikap Kiai Sahal ini tentu saja merupakan pelajaran berharga. Terutama dalam memahami bagaimana Kiai Sahal memaknai hakikat mencari ilmu, memandang pentingnya pendidikan untuk perempuan, memaknai relasi suami istri, serta bagaimana beliau mengapresiasi setiap usaha guna menyelesaikan pendidikan tepat waktu diantara aktivitas keluarga. Dukungan Kiai Sahal bagi pendidikan perempuan ini, tentu saja bukan yang pertama kali dilakukannya. Jauh sebelumnya, Kiai Sahal juga menunjukkan besarnya dukungan terhadap sang istri untuk menyelesaikan pendidikan tinggi, saat awal mula memasuki biduk rumah tangga.
Saat menikah, Nyai Nafisah Sahal adalah mahasiswi tingkat dua IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Meski keduanya bersepakat untuk menetap di Kajen pasca menikah, namun pada kenyataannya, Kiai Sahal tidak memaksa istrinya meninggalkan bangku kuliah setelah akad nikah terjadi. Justru sebaliknya, Kiai Sahal memberikan ruang bagi sang istri untuk tetap tinggal di Yogyakarta, melanjutkan kuliah hingga rampung dua tahun berikutnya.
Tentu bukan pilihan mudah bagi pasangan muda ini untuk melakoni kehidupan LDR (long distance relationship) dalam jangka waktu cukup lama. Terlebih, LDR itu terjadi bukan lantaran sang suami yang sedang menyelesaikan pendidikan tingginya. Tetapi justru sang istrilah yang sedang menyelesaikan kuliahnya. Dalam banyak kasus, dalam kedudukan suami yang tak menempuh bangku kuliah, tentu tak akan merelakan istrinya untuk menyelesaikan pendidikan tingginya pasca akad nikah. Dapat dibayangkan, bagaimana Kiai Sahal sudah memiliki pemikiran terdepan dalam mendukung perempuan untuk berpendidikan tinggi, bahkan pada saat banyak anak-anak perempuan lainnya tidak berkesempatan menyelesaikan pendidikan dasarnya. Wallalu A’lam.
Penulis:
Tutik N Jannah
Pendidik di Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah