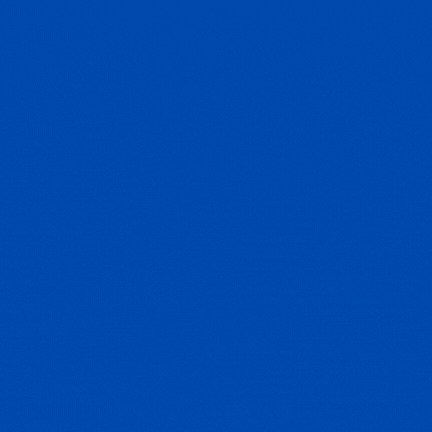Bulan Shafar tahun ini sudah hampir habis. Tak lama lagi ia akan meninggalkan kita. Tetapi bagi orang Jawa, bulan Shafar ini memiliki arti penting. Salah satunya karena bulan ini terdapat hari Rebo Wekasan. Sebagaimana yang kita tahu, Rebo Wekasan adalah nama bagi hari Rabu terakhir di bulan Shafar. Rebo Wekasan ini memiliki mitos yang cukup kuat bagi masyarakat Jawa, atau orang Indonesia pada umumnya.
Orang Jawa meyakini bahwa hari Rebo Wekasan adalah hari yang ‘singit’. Karena di hari tersebut diyakini terdapat macam-macam bala’ atau mara bahaya yang dapat mengancam kehidupan manusia. Karenanya, di hari ini, masyarakat diminta melakukan ritual-ritual khusus untuk menolak bala’ tersebut. Ada yang melakukan selametan, tradisi gunungan, sesajenan, dan lain-lain.
Di Sebagian tempat, tradisi ini sudah mengalami Islamisasi. Artinya, upacara selametan itu tidak lagi dilakukan dengan ritual-ritual sesajenan atau gunungan, melainkan telah diubah dengan melakukan shalat daf’ul bala’ dan bacaan-bacaan wirid dari para kiai. Lalu bagaimana sebenarnya ajaran Rebo Wekasan ini dalam pandangan Islam?
Selain merupakan keyakinan masyarakat Jawa, ternyata pengkramatan hari Rabu terakhir di bulan Shafar ini telah didapati sejak jahiliyah kuno. Masyarakat Jahiliyah meyakini bulan Safar sebagai bulan sial. Karena itu mereka banyak yang meninggalkan rumah atau mengosongkan desanya untuk keluar mencari keselamatan dari marabahaya. Lantaran tradisi itulah, maka bulan kedua hijriyah ini dinamakan shafar yang artinya kosong.
Tetapi keyakinan atas adanya sial pada bulan ini telah ditolak oleh Nabi dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari:
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ
“Nabi berkata : Tidak ada ada penularan penyakit (dengan sendirinya), tidak ada burung yang menunjukkan akan ada anggota keluarga yang mati, dan tidak ada kesialan di bulan shafar” (HR. Bukhari).”
Meski demikian tradisi itu tidak begitu saja bisa hilang dari kehidupan masyarakat Arab dan masyarakat-masyarakat di belahan bumi lain. Buktinya, hingga kini keyakinan akan adanya Rebo Wekasan dan turunnya bala’ pada hari ini terus saja masih kuat dalam tradisi masyarakat. Bahkan diantara ulama juga ada yang membenarkan keyakinan tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam kitab “Kanzun Najah wa al-Surur” oleh Syeikh Abdul Hamid Al Quddus, dan kitab “Khawajah Mughni al-Din” karya Syekh Syukur Kanji. Kedua ulama penulis kitab tersebut membenarkan bahwa berdsasarkan mukasyafah sebagian auliya’ membenarkan akan adanya bala’ pada hari Rabu terakhir di bulan Shafar itu. Di dalam kitab tersebut dikatakan bahwa pada hari Rabu terakhir bulan Shafar Allah menurunkan 320 ribu bencana. Sehingga hari itu dianggap hari tersulit selama setahun.
Karena itu ulama yang bersangkutan menganjurkan untuk berdoa dan shalat sunnah mutlak sebanyak empat rekaat yang diniatkan untuk menolak bala’. Pada shalat tersebut dianjurkan untuk membaca surat al-Kautsar 17 kali, al-Ikhlas 5 kali, al-Alaq 1 kali dan al-Nas 1 kali. Shalat sunnah mutlak itu kemudian dikenal di masyarakat sebagai shalat daf’ul bala’. Bahkan ada pula yang mengenalnya menjadi shalat Rebo Wekasan. Selain itu beliau juga menyarankan agar pada malam Rebo Wekasan itu umat Islam membaca surat Yasin. Khusus pada ayat “Salamun qaulan min rabin rahim” dibaca 313 kali dan diikuti oleh doa.
Ajaran inilah yang berkembang di masyarakat Jawa hingga sekarang. Karenanya, jika datang hari Rabu Wekasan, musholla-musholla dan masjid-masjid akan ramai menyiarkan shalat lidaf’il bala’ kepada para jamaahnya. Tetapi para kiai dan ulama sepakat bahwa shalat lidaf’il bala’ yang dilakukan pada Rabu Wekasan ini tidak boleh diyakini sebagai shalat yang disyari’atkan pada hari Rabu Wekasan. Karena hal itu tentu tidak sejalan dengan ajaran syari’at yang menyatakan bahwa asal ibadah adalah haram, hingga datang dalil yang membolehkannya.
Agama & Tradisi
Terlepas dari model perayaan dan peringatan masyarakat pada Rebo Wekasan, terdapat beberapa hal yang menarik dicermati dalam peringatan tersebut. Di Indonesia, para ulama’ dan para kiai menyepakati bahwa Rebo Wekasan bukanlah ajaran dalam agama. Tetapi para kiai juga tidak melakukan pelarangan terhadap keyakinan dan beberapa praktek tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pada hari Rebo Wekasan. Sikap inilah yang membedakan para ulama’ nusantara dengan ulama’ di tempat lain. Para ulama’ menyadari bahwa tidak semua tradisi yang berkembang di masyarakat selaras dengan syari’at. Tetapi juga tidak mungkin menghilangkan semua itu dari kehidupan masyarakat. Karena tradisi adalah bagian dari sejarah manusia. Dengan tradisi, manusia merasa ada dan mengenal dirinya. Karena itu sejak para Wali Songo hingga para ulama’ dan kyai saat ini, mereka lebih memilihi mendakwahkan syari’ah dengan tetap berdamai bersama tradisi yang berkembang di masyarakat. Para Kiai lebih memilih mengisi tradisi dengan ruh Syariah dibanding memerangi kebudayaan dan tradisi yang ada. Mereka mencoba memahami dan mengenali makna filosofis dari setiap praktek tradisi yang berkembang di lingkungan masyarakat.
Mengenali nilai filosofis pada tradisi dan budaya ini penting dilakukan dalam memahami budaya dan agama. Kehidupan beragama akan selalu berdampingan dengan budaya yang berbeda-beda. Ajaran agama yang telah baku dari Rasulullah melalui Quran dan Hadis, tidak akan mampu memahami kemajemukan budaya jika tidak ada upaya memahami nilai filosofis budaya tersebut. Akibatnya agama terjatuh pada tindakan memvonis atau men-judg terhadap praktek budaya yang dianggap tidak selaras dengan agama. Maka muncullah pelabelan bid’ah, khurafat, dan lain-lain pada praktek budaya yang berkembang di masyarakat.
Sebagai negara yang majemuk, Indonesia sangat kaya dengan kebudayaan dan tradisi yang dijaga dan lestarikan oleh masyarakat. Meski demikian dalam perjalanan sejarah Islamisasi di nusantara tidak ditemukan ketegangan yang berarti antara agama dan budaya. Keduanya dapat berjalan tanpa harus bersitegang satu dengan yang lain. Hal ini karena kearifan para auliya, ulama dan kiai yang mengajarkan kepada kita akan pentingnya menghargai kebudayaan leluhur dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Sunan Kudus menghargai keyakinan Hindu yang mendewakan sapi. Sehingga ia melarang orang Kudus untuk menyembelih sapi ketika korban. Sunan Kalijogo mengajarkan ketauhidan dengan menggunakan wayang dan gamelan. Ajaran wayang itu kemudian ia ubah dengan pesan-pesan ketauhidan melalui tembang dandang gulo dan lir-ilir. Upacara selametan dan ritual yang dilakukan pada upacara kematian tetap dilestarikan, tetapi dengan menggantinya dengan bacaan-bacaan kalimah thayyibah yang kita kenal sebagai tahlilan. Itulah teladan kearifan para wali dan ulama yang harus kita fahami. Agama dan budaya tidak harus bermusuhan, melainkan bisa saling mengisi dan berdampingan secara harmonis. Wallahu a’lam bisshawab.
Penulis:
Oleh: Umdah El Baroroh, Dosen IPMAFA dan Pendamping Santri Mansajul Ulum
Terbit Pada:
Kolom Jum'at IX Pondok Pesantren Mansajul Ulum, Cebolek Kidul, Pati, Jawa Tengah