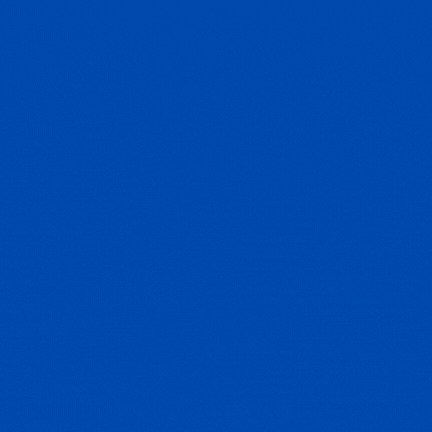Penulis: Adha Nafi'atur Rofiah/1804046069/KKN RDR 77 UIN Walisongo
Ketika berkumpul dengan warga di sekitar rumah saya, mereka kebetulan sedang membincangkan salah satu anak tetangga yang mengalami pemerkosaan oleh temannya. Salah satu warga menyeletuk "Kenapa nggak ditendang aja penisnya", "Kenapa nggak teriak minta tolong". Kalimat ini bahkan senada dengan yang dilontarkan penyidik kepolisian Amerika, saat mewawancarai korban, "Apakah kamu melakukan perlawanan?", "Apakah kamu berteriak meminta bantuan?". Scientific American mencatat bagaimana respon sangsi yang diberikan masyarakat bahkan aparat ketika penyintas pelecehan seksual berani speak-up. Pernyataan tersebut tentu menyakiti korban dan berpotensi membuatnya dikelilingi rasa bersalah. Tak ayal, seringkali korban memilih untuk bungkam karena merasa malu.
Padahal untuk mendapatkan keadilan, mereka harus bersuara. Butuh keberanian luar biasa untuk berbagi pengalaman menyakitkan, ditambah stigma masyarakat terhadap korban perkosaan yang dianggap tidak lagi 'suci'. Korban pasti berpikir berulang kali, sedangkan jiwanya terguncang karena peristiwa tersebut.
Bahkan, lebih menyedihkan lagi ketika aparat penegak keadilan tidak memberikan keberpihakan pada korban alih-alih mengambil keputusan yang adil. Seperti yang dilakukan Johnson, seorang hakim yang memangkas 10 tahun hukuman pelaku perkosaan, kekerasan, penguntitan, dan intimidasi yang dilakukan oleh Metin Gurel kepada mantan pacarnya. Dilansir dari Tirto.id, dalam putusannya, hakim Johnson berkata “Korban dalam kasus perkosaan ini, meskipun dia tidak menginginkannya, dia tidak melakukan perlawanan”.
Pertanyaan-pertanyaan di atas menyudutkan korban seolah-olah ia mau saja diperkosa. Kebungkamannya dianggap sebagai persetujuan tubuhnya ditelanjangi. Bagaimana bisa logika ini tercipta tanpa empati kepada korban. Ketidakberdayaan korban untuk melawan bukan berarti memperbolehkan dirinya dilecehkan, tetapi hal itu alami terjadi secara bio-psikologis ketika seseorang menghadapi ancaman. Meski manusia memiliki gerak refleks untuk melindungi diri, namun ketika ketakutan dan terguncang seseorang bisa saja mengalami kelumpuhan sementara. Jangankan berteriak, untuk bergerak saja terasa sangat berat dan kaku.
Fenomena tersebut dikaji secara mendalam oleh Acta Obstetrecia et Gynecologia Scandinavica (AOGS). Dalam penelitiannya kondisi seperti itu disebut Tonic Immobility (TI), yaitu ketidakmampuan tubuh untuk bergerak sebagai respon atas ancaman eksternal. Hewan pun mengalami kondisi serupa. Misalnya hewan oposum yang berpura-pura mati, tubuhnya melemas, kaki tertekuk, air liur menetes, dan mengeluarkan bau busuk. Oposum melakukannya sebagai mekanisme pertahanan diri terhadap mangsa. Pada manusia, TI dideskripsikan sebagai keadaan penghambatan motorik sementara yang tidak disengaja, sebagai respons terhadap situasi yang melibatkan rasa takut yang hebat. Lebih lanjut dijelaskan TI sebagai keadaan seperti katatonik dengan hiper atau hipotonisitas otot, tremor, kurangnya vokalisasi, analgesia dan relatif tidak responsif terhadap rangsangan eksternal. Hal ini alami dan spontan dialami manusia salah satunya ketika mengalami perkosaan.
Dalam penelitiannya AOGS memaparkan bahwa dari 10 sampel wanita, 7 diantaranya melaporkan imobilitas yang signifikan, hampir setengahnya melaporkan imobilitas ekstrim, dan 8 dari 10 melaporkan ketakutan yang signifikan selama serangan seksual. Bahkan orang yang mengalami TI dua kali lipat berisiko menderita post-traumatic stress disorder (PTSD) dan depresi berat.
Dari temuan beberapa penelitian yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa ketidakberdayaan korban untuk melawan merupakan respons alami tubuh, diluar kontrol diri. Oleh sebab itu tidak sepatutnya stigmatisasi terhadap korban pelecehan seksual dilakukan yang malah akan memperburuk kondisi psikologis mereka.
Tim redaksi: Edukratif News