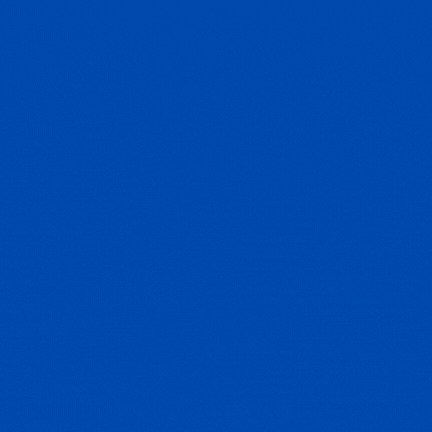EdukratifNews/Karya - Melihat raut wajah sang sahabat, Ainun sangat paham bahwa sedang ada yang mengganggu perasannya.
Dia duduk di sebelah Nana yang sedang berbaring di tempat tidur. Nana tak bersuara, padahal biasanya langsung menyambut kedatangan Ainun dengan kalimat tanya "Kok gak bilang kalau mau ke sini?" seraya tersenyum bahkan juga tawa.
Namun kali itu berbeda. Apakah gerangan yang membuat Nana mengunci rapat bibirnya dan memaku kaku wajahnya dari senyuman yang biasa terhias di sana?
"Kamu kenapa?" Ainun mulai bertanya.
Namun Nana tak juga bersuara. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Matanya mulai berair kemudian mengalir dari sudut mata kanannya. Dia mengusapnya segera. Kini Ainun makin yakin bahwa Nana sedang sedih tapi ia tak lagi berani bertanya kenapa untuk yang kedua kalinya.
Suara deru kipas angin di kamarnya makin menambah suasana riuh tapi sendu dalam hati. Nana tak kuat menahan kesedihannya, dia terus menangis dengan posisi telungkup. Dia menutup kepalanya dengan bantal dan menangis sejadi-jadinya. Ainun mulai bingung, apa yang harus dia lakukan, akhirnya diam seribu bahasa hanya menunggu dengan setia di sisi sang sahabat sampai ia mau curhat.
Niat dari rumah ingin curhat dan minta pendapat ternyata harus Ainun tunda untuk sementara waktu. Sebab orang yang biasanya menjadi pendengar sekaligus penasihat itu nampaknya sedang terluka, entah apa penyebabnya belum terungkap. Namun Ainun yakin, setelah ini Nana pasti cerita, hanya saja butuh waktu untuk menangis terlebih dahulu, mengurangi beban batinnya yang sedang riuh menggerutu.
"Saya sedih." Nana mulai bicara. Setelah posisi tubuhnya berubah dari yang tadinya telungkup, sekarang miring ke kanan menghadap barat sambil memeluk bantal. Sementara Ainun masih standbye duduk di sampingnya.
"Kenapa? Ada apa?" Tanya Ainun.
"Tadi pagi saya coba pamit ke ibu"
"Perihal apa?"
"Saya pengen mondok"
"Terus?"
"Saya sedih, sangat sedih, ketika ibu bilang 'terus ibu akan dapat uang biaya mondokmu dari mana, Nak?' gitu." Suara Nana terhenti dalam lirihnya. Air matanya kembali mengalir. Tisu di tangannya sudah tak menemukan kondisi kering. Seluruhnya basah.
Ainun juga bingung mau jawab apa. Dia pun termangu.
"Bukankah selama ini kamu kuliah itu biaya sendiri." Kata ibu.
"Itu beasiswa buk"
"Iya, dan penghasilanmu sendiri kamu kasih ke ibuk untuk belanja. Terus kalau mondok, apakah ada beasiswa juga? Berarti harus berhenti dari pekerjaanmu, mau berhenti selamanya, atau hanya cuti? Kalau cuti apakah nanti kamu bisa balik lagi ke posisi jabatan yang sekarang?"
Nana menuturkan kepada Ainun tentang apa yang dikatakan ibunya.
"Saya sedih, kenapa saya ada di posisi yang seolah menghalangi saya mendapat Ridha ibu untuk mendalami ilmu agama?"
Ainun mulai tak tega melihat air mata sahabatnya yang terus mengalir tanpa henti. Dia paling tidak sanggup melihat Nana bersedih apalagi sampai menangis. Nana bukan perempuan yang cengeng, sangat jarang dia terlihat bersedih, murung apalagi menangis. Dia pernah punya masalah berat yang menurut Ainun andai terjadi pada Ainun mungkin bisa jadi frustasi, tapi Nana menghadapinya dengan penuh ketegaran. Dia tak pernah menampakkan air matanya di depan siapa pun. Baru kali ini Nana terlihat sesedih dan serapuh ini. Seolah dunia adalah musuhnya.
"Ini memang sulit, tidak hanya sebatas persoalan seseorang yang haus akan ilmu. Kamu punya dunia di sini. Kamu punya jabatan, profesi, penghasilan, itu juga kamu peroleh karena ilmu yang sudah ada padamu. Posisi kamu yang sekarang adalah kebanggaan bagi orang tuamu. Banyak orang yang menginginkan ada di posisimu ini, tentu ibumu berat jika semua itu kamu lepas." Kata Ainun.
"Itulah masalahnya. Saya terlanjur berada di depan, dan saya tidak bisa kembali ke belakang, padahal saya punya banyak sekali ketertinggalan. Dan banyak yang harus saya perbaiki menuju masa depan."
"Menurutku sebenarnya kamu hanya kurang aja. Merasa haus aja dengan ilmu. Makanya merasa tertinggal dan semacamnya. Bagiku kamu sudah luar biasa. Bekal dasarmu sudah cukup"
"Kamu kok malah ikutan bilang bekalku sudah cukup? Ilmu agamaku masih minim sekali, kamu gak tahu betapa aku tertinggal jauh di usia segini, belum hafal 1 jus Al Qur'an saja. Kamu gak lihat, di luar sana anak2 usia 5, 6, 7, sudah hafal beberapa jus." Nana ngegas, suaranya meninggi, matanya membinar, nampaknya jiwanya mulai tak stabil, dia mulai marah, dan Ainun menjadi satu-satunya santapan emosinya siang ini.
"Saya malu sama mereka. Bagaimana nanti harus kutemui sayyidah Fatimah, jika diriku tak sanggup bersahabat dengan ayat-ayat suci-Nya. Padahal lihat usiaku sekarang! Lihat! Berapa? Jika usiaku tidak sampai 60 tahun tentu bukan 50% lagi yang tersisa. Saya sudah ketinggalan banyak. Dan saya bingung sekarang." Nana melanjutkan ungkapan emosinya.
"Saya gak apa-apa kehilangan semua ini, tapi saya tidak bisa melangkah tanpa restu ibu. Saya gak butuh semua ini Aiiiiiii, ilmu bagiku jauh lebih berharga daripada jabatan dan profesiku saat ini, tapi ibuku berat jika saya melepas semuanya. Saya harus gimana?
Intonasi Nana terdengar semakin dalam, Ainun diam saja, dia malah ikutan menangis, tak tega dengan tangisan Nana yang benar-benar baru kali ini tampak sangat memberatkan. Ainun tak tahu harus membela dengan jawaban apa. Emosi sahabatnya sedang meluap. Entah dia sebenarnya marah pada siapa. Pada diri sendirikah? Atau pada Ainun?
Lalu Nana diam. Ainun pun sama. Kamar itu menjadi senyap seketika. Suasana menjadi hening sampai sekitar 30 menit. Sampai akhirnya sang ibu memanggil. Nana turun dari tempat tidurnya tanpa menjawab panggilan ibu dia langsung menghapirinya walau dia sendiri tahu maksud sang ibu memanggil adalah untuk menyuruhnya agar mengajak Ainun makan siang.
Sesekali, Nana terdiam. Menatap lekat wajah ibu yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Dalam hati ia berlirih dengan penuh pengharapan, "Ibu, engkau hanya butuh pemahaman, bahwa dunia ini tak berarti apa pun bagi anakmu. Jika nanti Abang bisa meyakinkan hatimu, bahwa keinginanku lebih benar daripada pemahamanmu yang masih terpengaruh lingkungan, maka selanjutnya tugasku adalah mencari biaya sendiri untuk kembali menjadi santri di pesantren. Sungguh anakmu ini tak ingin sedikitpun membebanimu dengan finansial." Air matanya kembali menetes dan segera diseka agar tak seekor semut pun melihatnya. "Ya Allah, sungguh banyak sekali tugasku. Bantu aku" lanjutnya dalam hati dan pikiran.
Sumber: Facebook Nora
Edukratif News
Pasang Iklan: Klik Disini